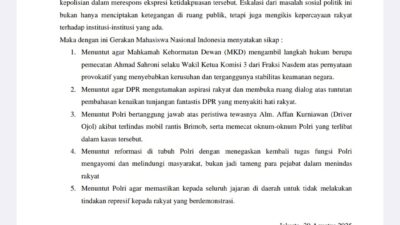Monwnews.com, Di podium kehormatan, atlet berdiri sendiri. Di belakang layar, sistem berdiri bersama—namun tak selalu berpihak. Setiap medali yang diraih atlet Indonesia selalu disambut sorak sorai nasionalisme. Negara bertepuk tangan, pejabat hadir memberi ucapan selamat, dan publik diyakinkan bahwa pembinaan olahraga nasional berjalan di jalur yang benar. Namun di balik euforia itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan secara terbuka: apakah sistem pembinaan olahraga prestasi benar-benar bekerja untuk atlet, atau justru nyaman bagi segelintir elite pengelola?

Tulisan ini bukan menuduh individu atau lembaga tertentu. Ini adalah pembacaan kritis atas pola tata kelola—sebuah investigative feature berbasis kebijakan publik—yang menunjukkan bagaimana olahraga prestasi Indonesia berisiko terjebak dalam elite capture: penguasaan anggaran, kewenangan, dan legitimasi oleh kelompok terbatas, tanpa akuntabilitas publik yang memadai.
Negara Membiayai, Tapi Tak Mengendalikan Sepenuhnya
Secara formal, negara hadir. Pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran dari APBN dan APBD untuk olahraga prestasi—mulai dari pembinaan, pemusatan latihan, hingga penyelenggaraan kejuaraan. Namun, pelaksanaan teknis pembinaan banyak dijalankan oleh organisasi olahraga yang bersifat mandiri, berbasis keanggotaan, dan relatif tertutup.
Model ini tidak sepenuhnya keliru. Di banyak negara, negara memang tidak mengelola detail teknis pembinaan atlet. Organisasi olahraga dianggap lebih memahami kebutuhan cabang masing-masing. Masalah muncul ketika uang publik mengalir tanpa diikat oleh kontrak kinerja yang ketat.
Akibatnya, negara menanggung risiko fiskal, sementara kontrol operasional dan informasi berada di luar jangkauan publik. Ketika prestasi naik, keberhasilan diklaim kolektif. Ketika prestasi turun, tanggung jawab menjadi kabur.
Elite Capture: Bukan Skandal, Melainkan Pola Sistemik
Elite capture dalam olahraga jarang muncul sebagai skandal hukum. Ia bekerja senyap, legal secara formal, tetapi problematik secara tata kelola. Polanya berulang: struktur organisasi yang relatif stagnan, pengambilan keputusan yang terkonsentrasi, transparansi anggaran yang administratif, serta evaluasi program yang lebih menekankan kepatuhan prosedural ketimbang dampak prestasi.
Semua tampak “sesuai aturan”. Namun justru di situlah masalahnya: aturan itu sendiri tidak cukup keras menuntut akuntabilitas kinerja. Dalam situasi ini, olahraga prestasi berisiko berubah dari sistem pembinaan menjadi ekosistem pengelolaan kewenangan.
Atlet: Output Sistem, Bukan Subjek Keputusan
Atlet berada di ujung rantai. Mereka adalah wajah prestasi, tetapi nyaris tak punya suara dalam pengambilan keputusan. Ketika gagal, atlet dan pelatih disorot. Ketika berhasil, legitimasi mengalir ke struktur.
Banyak atlet Indonesia berprestasi bukan karena sistem yang unggul, melainkan karena daya tahan pribadi, sokongan keluarga, dan pengorbanan pelatih. Narasi ini sering dipuja sebagai kisah inspiratif. Namun dalam kacamata kebijakan publik, ini adalah indikasi kegagalan sistemik: prestasi lahir dari pengecualian, bukan dari sistem yang dapat direplikasi.
Anggaran APBN/APBD dan Pemborosan Struktural
Persoalan menjadi lebih serius ketika ditelusuri melalui anggaran. Setiap tahun, dana publik yang tidak kecil dialokasikan untuk olahraga prestasi. Namun tanpa kontrak kinerja berbasis hasil, anggaran ini rentan terhadap pemborosan struktural.
Pemborosan struktural berbeda dari korupsi. Ia tidak selalu melanggar hukum, tetapi menggerogoti efektivitas. Bentuknya antara lain program yang tumpang tindih, kegiatan seremonial berulang, rapat dan perjalanan yang minim korelasi dengan peningkatan prestasi, serta pembinaan yang tidak terhubung dalam jalur jangka panjang.
Dalam kondisi fiskal yang semakin ketat—ketika anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial saling berebut ruang—pemborosan struktural di sektor olahraga bukan sekadar soal efisiensi, melainkan soal keadilan penggunaan uang negara.
Ilusi Otonomi dan Ketakutan Mengoreksi
Salah satu hambatan utama pembenahan tata kelola olahraga adalah ketakutan negara untuk menertibkan sistem. Otonomi organisasi olahraga sering diperlakukan sebagai wilayah sakral. Setiap upaya penguatan kontrol dianggap intervensi.
Padahal, di banyak negara, otonomi justru berjalan berdampingan dengan disiplin evaluasi. Otonomi tanpa pengawasan hanya memindahkan risiko dari negara ke atlet. Ironisnya, organisasi tetap otonom dari kontrol publik, tetapi bergantung pada uang publik.
Cermin dari Luar Negeri
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa prestasi olahraga dibangun dengan disiplin tata kelola. Inggris mengikat pendanaan elite sport melalui kontrak kinerja multi-tahun. Australia menempatkan negara sebagai investor dan pengarah sistem, dengan kejelasan peran. Amerika Serikat menekan akuntabilitas melalui mekanisme non-negara.
Modelnya berbeda, tetapi benang merahnya sama: tidak ada ruang nyaman tanpa evaluasi.
Masalah Utama: Disiplin, Bukan Dana
Narasi bahwa olahraga Indonesia tertinggal karena kekurangan anggaran perlu dikoreksi. Masalah utamanya bukan jumlah dana, melainkan ketiadaan disiplin tata kelola. Tanpa peta jalan prestasi yang jelas, anggaran hanya memperpanjang umur struktur, bukan mempercepat lahirnya juara.
Elite capture menciptakan ilusi stabilitas administratif, sementara sistem di lapangan tetap rapuh.
Policy Warning: Mengunci Sistem Sebelum Terlambat
Jika dibiarkan, elite capture berisiko menimbulkan tiga dampak serius: prestasi tidak konsisten, atlet kehilangan kepercayaan, dan publik mempertanyakan legitimasi pembiayaan olahraga prestasi.
Karena itu, peringatan kebijakan perlu ditegaskan: dana publik harus diikat kontrak kinerja, audit kinerja harus independen dan terbuka, data pembinaan harus transparan, dan peran negara–organisasi harus dipisahkan tegas.
Penutup
Olahraga prestasi adalah cermin tata kelola negara. Jika sistemnya tertutup dan nyaman bagi elite sempit, prestasi hanya akan lahir secara sporadis. Jika sistem dibangun transparan dan disiplin, prestasi akan menjadi hasil yang berkelanjutan.
Indonesia tidak kekurangan atlet berbakat. Yang dipertaruhkan adalah keberanian menertibkan sistem yang selama ini terlalu nyaman untuk disentuh.
Pertanyaannya sederhana:
olahraga ini dikelola untuk atlet dan bangsa, atau untuk menjaga kenyamanan struktur?