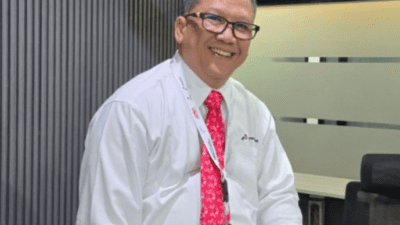Monwnews.com, Demokrasi liberal gemar menyebut dirinya sistem yang paling tahan terhadap kebohongan. Ia percaya pada transparansi, debat terbuka, dan koreksi publik. Namun pengalaman menunjukkan paradoks yang berulang: justru di dalam demokrasi liberal, terdapat topik-topik yang tidak pernah benar-benar dilarang, tetapi juga tidak pernah boleh dibahas secara tuntas. Bukan karena kurang data, melainkan karena terlalu banyak kepentingan yang terancam bila pembicaraan dilanjutkan.

Tulisan John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, berada tepat di wilayah abu-abu itu. Ia tidak mengungkap rahasia negara, tidak membocorkan dokumen ilegal, dan tidak menuduh konspirasi. Namun reaksinya menyerupai respons terhadap sebuah pelanggaran serius. Bukan pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran terhadap batas tak tertulis dalam demokrasi liberal Amerika: jangan terlalu jauh membedah mekanisme kekuasaan sendiri.
Bagi Indonesia, yang mengklaim politik luar negeri bebas dan aktif, kisah ini lebih dari sekadar polemik akademik Amerika. Ia adalah studi kasus tentang bagaimana kekuasaan bekerja secara senyap, dan bagaimana demokrasi dapat membatasi dirinya sendiri tanpa perlu alat represi klasik.
Pola yang Terlihat, tetapi Jarang Dibicarakan
Argumen utama Mearsheimer dan Walt sederhana: kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah tidak sepenuhnya ditentukan oleh kalkulasi kepentingan nasional strategis, melainkan sangat dipengaruhi oleh kekuatan domestik yang terorganisasi dengan baik—yang mereka sebut Israel Lobby. Mereka menjelaskan bagaimana lobi bekerja melalui jalur yang sepenuhnya legal: Kongres, pendanaan politik, think tank, media, dan tekanan wacana.
Yang menarik, hampir tidak ada bantahan serius terhadap data inti mereka. Bantahan lebih sering datang dalam bentuk pertanyaan niat: mengapa topik ini diangkat?, apa motifnya?, siapa yang diuntungkan? Di sinilah pola mulai terlihat. Ketika kritik terhadap kebijakan berubah menjadi kritik terhadap struktur pengaruh, demokrasi liberal cenderung berhenti berdiskusi dan mulai menilai karakter.
Ini bukan soal Israel semata. Ini soal mekanisme umum: demokrasi tidak alergi pada kritik, selama kritik itu tidak mengganggu konsensus strategis yang sudah mapan.
Sensor yang Tidak Pernah Mengaku Sensor
Tidak ada larangan resmi atas tulisan ini. Namun setelah terbit, yang muncul adalah rangkaian reaksi khas: tuduhan anti-Semitisme, tekanan institusional di kampus, delegitimasi akademik, dan upaya memindahkan perdebatan dari substansi ke moralitas. Ini bukan kebetulan, melainkan teknik lama dalam politik modern.
Sensor demokratis tidak bekerja dengan menutup mulut. Ia bekerja dengan menaikkan ongkos berbicara. Ketika sebuah topik selalu diikuti risiko reputasi, karier, dan stigma moral, mayoritas orang akan memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau membayar harga sosialnya.
Dalam konteks ini, demokrasi liberal tampak tidak sepenuhnya percaya pada kekuatan argumen. Ia lebih percaya pada pengelolaan batas wacana.
Dari Washington ke Dunia: Dampak Global Politik Domestik
Tulisan ini membuka satu fakta yang sering diabaikan negara-negara Global South: kebijakan luar negeri negara adidaya kerap merupakan hasil kompromi politik domestik, bukan refleksi nilai universal. Artinya, ketika standar ganda diterapkan di forum internasional—misalnya dalam isu Palestina—itu bukan anomali, melainkan konsekuensi dari struktur politik internal negara besar.
Indonesia sering menempatkan diri sebagai pembela hukum internasional dan keadilan global. Namun tanpa pemahaman tentang politik domestik negara adidaya, posisi itu mudah berubah menjadi sekadar sikap moral, bukan strategi. Kita berbicara tentang keadilan, sementara keputusan nyata diambil berdasarkan kalkulasi elektoral di Washington.
Politik luar negeri bebas-aktif seharusnya tidak berhenti pada keberpihakan normatif. Ia menuntut kemampuan membaca siapa yang sebenarnya memegang tuas keputusan, dan mengapa tuas itu bergerak ke arah tertentu.
Demokrasi yang Rentan pada Distorsi
Reaksi terhadap karya Mearsheimer–Walt juga mengungkap kelemahan mendasar demokrasi liberal: ketergantungannya pada kelompok kepentingan yang intens. Ketika mayoritas publik tidak terlalu peduli pada isu luar negeri, kelompok kecil yang sangat terorganisasi dapat mengisi ruang kosong itu. Ini bukan penyimpangan, melainkan fitur sistem.
Masalah muncul ketika sistem menolak mengakui distorsi tersebut. Alih-alih membahas bagaimana kebijakan bisa terseret jauh dari kepentingan publik, diskursus publik diarahkan untuk mempertahankan ilusi bahwa semua berjalan normal. Kritik dianggap ancaman, bukan peringatan.
Bagi Indonesia, ini relevan bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai pelaku demokrasi. Apakah kita yakin kebijakan luar negeri dan strategis kita kebal dari pola serupa? Ataukah kita hanya belum cukup jujur untuk mengakuinya?
Kampus dan Penertiban Wacana
Salah satu bagian paling mengkhawatirkan dari kisah ini adalah reaksi di dunia akademik Amerika. Upaya pengawasan kampus, pelabelan dosen, hingga tekanan pendanaan menunjukkan bahwa bahkan ruang yang paling sering dipuji sebagai benteng kebebasan berpikir pun memiliki garis merah.
Jika pengetahuan yang tidak nyaman harus selalu dibela dengan biaya personal yang tinggi, maka kebebasan akademik tinggal slogan. Indonesia perlu bercermin. Ketika riset atau kajian menyentuh kepentingan besar—baik asing maupun domestik—apakah negara dan masyarakat akan melindunginya, atau justru ikut menekan atas nama stabilitas?
Negara yang takut pada pengetahuan kritis akan selalu kalah dalam pertarungan narasi global.
Solidaritas, Moralitas, dan Manipulasi Batas
Tulisan ini sering ditolak dengan argumen moral: bahwa kritik terhadap pengaruh Israel Lobby akan melemahkan solidaritas terhadap korban anti-Semitisme. Ini argumen yang efektif secara emosional, tetapi problematik secara intelektual. Ia menyamakan kritik terhadap kebijakan dan struktur pengaruh dengan kebencian terhadap identitas.
Demokrasi yang matang seharusnya mampu membedakan keduanya. Namun justru di sinilah garis tabu dijaga: ketika pemisahan itu tidak diizinkan, maka moralitas berubah menjadi alat disiplin wacana.
Penutup: Bebas-Aktif atau Aktif Menghindar?
Kisah The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy bukan hanya tentang Amerika dan Israel. Ia adalah peringatan tentang bagaimana demokrasi modern mengelola ketidaknyamanan. Bukan dengan larangan, tetapi dengan membuat sebagian kebenaran terlalu mahal untuk diucapkan.
Bagi Indonesia, pertanyaan akhirnya sederhana: apakah politik luar negeri bebas-aktif kita disertai keberanian untuk memahami realitas kekuasaan apa adanya? Ataukah kita hanya bebas berbicara sejauh tidak mengganggu narasi dominan, dan aktif selama aman secara politik?
Dalam dunia yang semakin dipenuhi retorika nilai, mungkin kedaulatan sejati bukan terletak pada keberanian memilih pihak, melainkan pada keberanian membaca pola kekuasaan di baliknya—bahkan ketika pengetahuan itu tidak nyaman, tidak populer, dan nyaris “dilarang”.