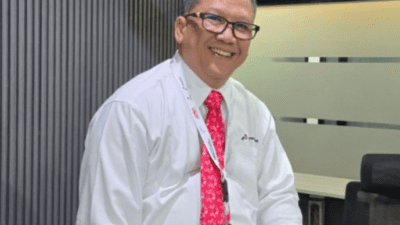Demokrasi kadang tidak mati oleh kudeta. Ia melemah oleh tepuk tangan. Institusi pelan-pelan diturunkan dari singgasana, diganti oleh sorak kepada figur. Di situlah hukum berubah menjadi properti, dan kebijakan menjelma atraksi. Kita menyaksikannya kini—secara terang, nyaring, dan disiarkan langsung.
Monwnews.com, Ada pergeseran sunyi dalam politik global, dan kita sering keliru membacanya sebagai sekadar gaya kepemimpinan. Padahal yang berubah bukan gaya, melainkan sumber legitimasi. Pada era ini, kekuasaan tidak lagi membutuhkan institusi sebagai pusat pembenarannya. Ia cukup memiliki figur, panggung, dan publik yang terbelah. Dalam lanskap seperti itu, prosedur dianggap lamban, pengawasan dianggap gangguan, dan kesepakatan internasional dinilai sebatas kontrak dagang yang bisa dibatalkan bila tidak lagi menguntungkan. Politik menjadi tontonan, sementara negara berubah menjadi properti reputasi pemimpinnya. Fenomena itu menemukan bentuk paling vulgar sekaligus paling efektif dalam diri Donald Trump. Yang kita lihat bukan sekadar populisme, melainkan sesuatu yang lebih tua usianya daripada republik modern: kebangkitan kembali naluri kerajaan, hidup nyaman di dalam kulit demokrasi.

Politik sebagai Atraksi
Apa yang sering disebut keberanian melawan kemapanan sebenarnya bekerja dengan cara yang jauh lebih sederhana: membangun hubungan langsung antara pemimpin dan massa, sambil mengikis semua perantara yang bernama institusi. Pengadilan, parlemen, birokrasi, pers, pakar—mereka tidak lagi menjadi fondasi legitimasi, melainkan bagian dari dekor yang boleh dipuji, boleh juga dihina.
Di situ, konflik bukan masalah. Ia bahan bakar. Setiap kritik membantu mempertebal narasi bahwa pemimpin adalah korban konspirasi. Setiap prosedur yang menghambat akan dipamerkan sebagai bukti keberanian melawan sistem. Politik berhenti menjadi proses deliberasi; ia berubah menjadi teater.
Kita hidup pada zaman ketika pidato bukan lagi penjelasan kebijakan, tetapi produksi emosi. Kebenaran tidak diukur dari verifikasi, melainkan dari viralitas. Dan di atas panggung semacam ini, figur yang paling piawai menciptakan kegaduhan hampir selalu menang.
Dari Republik ke Persona
Neo-royalisme bekerja dengan satu trik lama: membuat negara menyusut menjadi pribadi. Seolah kepentingan nasional identik dengan kehendak pemimpin. Seolah stabilitas sama dengan loyalitas kepada figur. Seolah kritik adalah ancaman terhadap keselamatan bangsa.
Dalam tata politik modern, institusi diciptakan untuk mencegah penyempitan itu. Ada pemisahan kekuasaan, ada mekanisme kontrol, ada prosedur. Semua dirancang agar negara tidak berubah menjadi milik seseorang.
Tetapi ketika persona lebih dipercaya daripada prosedur, maka logika berbalik. Aturan dianggap bisa dinegosiasikan. Komitmen bisa direvisi. Bahkan sekutu pun diperlakukan seperti pelanggan yang bisa ditagih ulang.
Dunia Menjadi Transaksi
Di panggung internasional, konsekuensinya brutal. Tatanan berbasis aturan pelan-pelan kehilangan daya ikat. Yang muncul adalah diplomasi berbasis kedekatan, forum undangan, kesepakatan ad-hoc. Legitimasi lahir bukan dari mandat kolektif, melainkan dari siapa yang duduk di meja makan.
Model ini menciptakan dunia yang tampak dinamis tetapi sebenarnya rapuh. Komitmen berubah mengikuti siklus politik domestik. Perjanjian bisa dibatalkan lewat satu konferensi pers. Kepercayaan—mata uang terpenting dalam hubungan internasional—tergerus sedikit demi sedikit.
Bagi negara kuat, fleksibilitas ini menyenangkan. Bagi negara berkembang, ini mimpi buruk. Ketika aturan melemah, yang berbicara adalah daya tekan. Tarif, sanksi, pembatasan teknologi, akses pasar—semuanya menjadi alat negosiasi yang sah.
ASEAN di Bawah Sorotan
Kawasan Indo-Pasifik merasakan getarannya paling cepat. Negara-negara dihadapkan pada pilihan yang makin sempit: ikut arus atau menanggung risiko. Otonomi strategis menjadi mahal karena setiap jarak dari kekuatan besar dibaca sebagai ketidaksetiaan.
Di situ, solidaritas regional diuji. Apakah tetap berdiri bersama, atau masing-masing bernegosiasi sendiri demi keuntungan jangka pendek. Neo-royalisme global mendorong fragmentasi, sebab hubungan personal lebih mudah dikelola daripada posisi kolektif.
Penularan ke Dalam Negeri
Bahaya terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari godaan untuk meniru. Ketika politik atraksi terlihat efektif, banyak yang ingin mempraktikkannya. Mengapa repot membangun institusi jika karisma lebih cepat menghasilkan tepuk tangan?
Padahal sejarah pembangunan berkata sebaliknya. Investasi tumbuh karena kepastian hukum, bukan karena kedekatan dengan penguasa. Inovasi lahir dari meritokrasi, bukan patronase. Negara kuat berdiri di atas prosedur yang bisa dipercaya, bukan pada suasana hati pemimpin.
Neo-royalisme menjanjikan efisiensi jangka pendek. Tetapi ia menyimpan ongkos jangka panjang: korupsi yang sulit disentuh, kebijakan yang berubah-ubah, dan masyarakat yang kehilangan pegangan tentang apa yang benar.
Ketika Demokrasi Menjadi Abu-Abu
Pemilu tetap ada. Partai tetap berjalan. Media masih terbit. Namun substansi menyusut. Demokrasi berubah menjadi ritual legitimasi, bukan mekanisme kontrol. Kekuasaan terlihat sah, tetapi tidak lagi terkendali.
Inilah wilayah abu-abu itu. Tidak diktator, tetapi juga bukan demokrasi yang sehat. Sebuah ruang di mana pemimpin bisa berkata: saya dipilih rakyat, maka saya adalah negara.
Apa Artinya bagi Indonesia
Bagi Indonesia, tantangannya nyata.
Pertama, risiko ekonomi. Dalam dunia yang makin transaksional, ketergantungan pada satu pasar atau satu sumber teknologi adalah kerentanan politik. Keputusan bisa datang tiba-tiba, tanpa proses panjang yang dulu kita kenal.
Kedua, risiko keamanan. Tekanan untuk memilih blok dapat menyempitkan prinsip bebas-aktif. Negara menengah seperti Indonesia membutuhkan ruang manuver; tanpa itu, diplomasi berubah menjadi reaksi.
Ketiga, risiko domestik. Politik atraksi mudah menggoda karena hasilnya cepat terlihat. Tetapi begitu institusi dilemahkan, memulihkannya jauh lebih sulit.
Jalan Bertahan
Menghadapi dunia neo-royalis bukan berarti ikut menjadi kerajaan kecil. Jawabannya justru memperkeras republik.
Institusi harus dibuat lebih tahan terhadap personalisasi. Mekanisme pengawasan mesti independen. Regulasi ekonomi harus stabil dan dapat diprediksi. Tanpa itu, kita selalu berada dalam posisi tawar yang lemah.
Otonomi strategis juga harus nyata. Diversifikasi mitra dagang, penguatan industri bernilai tambah, dan diplomasi rantai pasok adalah cara membuat Indonesia terlalu penting untuk ditekan.
Di tingkat internasional, kerja sama dengan sesama negara menengah menjadi penyangga. Ketika kekuatan besar berubah-ubah, solidaritas horizontal memberi napas.
Publik sebagai Warga, Bukan Penonton
Neo-royalisme tumbuh subur di masyarakat yang terbelah informasi. Karena itu, transparansi kebijakan dan literasi publik menjadi benteng utama. Rakyat harus diberi data, bukan hanya slogan. Penjelasan, bukan sekadar pertunjukan.
Demokrasi membutuhkan warga yang berpikir. Tanpa itu, ia mudah berubah menjadi festival popularitas.
Mahkota atau Konstitusi
Pada akhirnya, pertarungan ini sederhana: apakah legitimasi berada di kepala seseorang, atau di dalam aturan bersama. Yang pertama memberi drama. Yang kedua memberi kepastian.
Indonesia tidak punya kemewahan untuk memilih drama. Pembangunan membutuhkan stabilitas yang rasional. Keadilan sosial memerlukan birokrasi yang bekerja, bukan panggung yang riuh.
Jika dunia memang bergerak menuju neo-royalisme, maka tugas kita bukan ikut menari. Tugas kita menjaga agar konstitusi tetap lebih tinggi daripada mahkota—betapapun memesonanya sorot lampu itu.